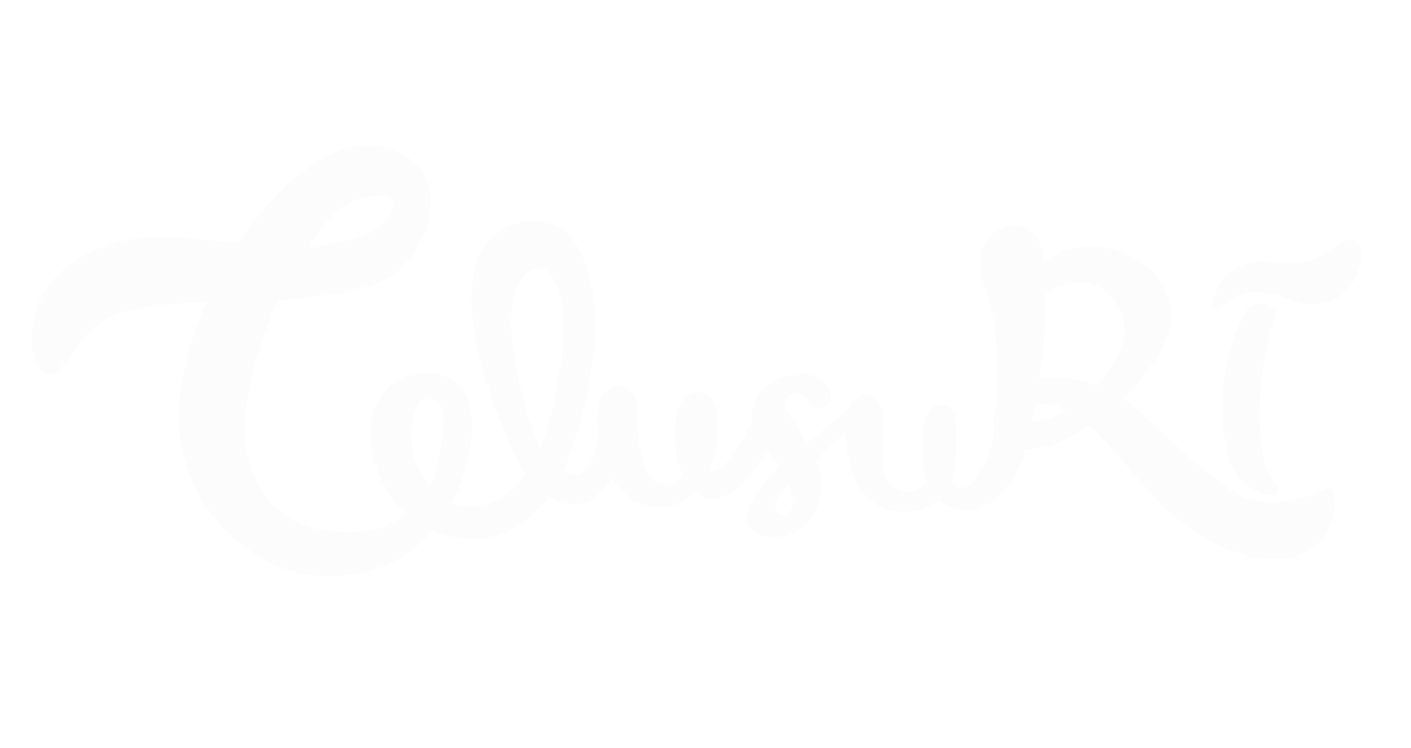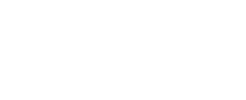Siang itu, aku terpaku pada sebuah poster di Instagram bertuliskan Banyuwangi Traditional Ritual Syawal. Di atasnya, terselip kalimat “Kisah leluhur dalam doa, tarian, dan sebuah janji yang tak tergoyahkan”. Tiga nama menonjol di sana, yaitu Seblang Olehsari, Barong Ider Bumi, dan Puter Kayun Boyolangsu Culture Festival. Namun, satu yang paling menyita rasa penasaranku: Seblang Olehsari. Tarian sakral yang dibawakan oleh gadis terpilih secara supranatural.
Hal yang membuatku semakin tergerak, ritual ini berlangsung selama seminggu penuh, 4–10 April 2025, dimulai pukul 14.00 WIB, dan dilaksanakan tepat pada hari keempat Lebaran Idulfitri. Mengapa bisa selama itu? Apa yang ingin dijelaskan melalui tarian ini? Mengapa hanya satu perempuan yang menari? Dalam foto-foto lama yang beredar, sang penari tampak menari dengan mata terpejam—seakan tubuhnya menjadi medium yang disinggahi suara dari masa lalu.
Aku pun memutuskan menyusuri jejak rasa ingin tahu ini, dari Jakarta ke Banyuwangi. Lokasi pagelaran Seblang Olehsari bertempat di Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, di lingkungan masyarakat Suku Osing. Setibanya di kabupaten paling timur Pulau Jawa, aku dan empat temanku berangkat ke lokasi dengan sepeda motor.
Kami tiba sekitar pukul tiga sore. Parkiran sudah padat. Langkah kami tersendat oleh kerumunan yang mengular di pintu masuk arena. Aku tertegun. Untuk sebuah tarian? Sebanyak ini orang berkumpul? Dalam dunia yang serba cepat ini, bagaimana bisa sebuah ritual bertahan? Di tengah keramaian, aku sempat berbincang ringan dengan beberapa pengunjung. Banyak di antaranya ternyata datang dari luar Banyuwangi.


Apa itu Seblang Olehsari?
Seblang adalah upacara ritual bersih desa atau selamatan desa yang diselenggarakan setahun sekali, dan kemungkinan dianggap sebagai pertunjukan tertua di Banyuwangi (Scholte, J., 1927:149–150; Wolbers, P.A., 1992:89; 1993:36). Masyarakat setempat percaya bahwa setelah melaksanakan kegiatan ritual, hidup terasa lebih tenteram, terhindar dari gangguan roh-roh halus, dan hasil panen pun menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika upacara tidak diselenggarakan, diyakini akan terjadi disharmoni dan keseimbangan ekologi akan terganggu, seperti gagal panen atau serangan wabah penyakit (Anoegrajekti, 2003:258).
Seblang Olehsari bukan sembarang tarian. Hanya perempuan suci dari garis keturunan penari Seblang yang bisa membawakannya. Penari akan berganti setiap tiga kali pergelaran. Selama tujuh hari berturut-turut, ia menari dari siang hingga petang. Hari itu, aku menyaksikan rangkaian ritual ini hingga sekitar pukul 17.40 WIB.
Ia menari dalam keadaan trance (kesurupan), mata tertutup. Di sekelilingnya ada pengiring, asap dupa, mantra, sinden dan gamelan, serta hal lain yang belum kutahu rinci penyebutannya. Sekitar 30 menit setelah aku tiba, penari telah mulai mengelilingi panggung, lalu naik ke atas panggung kecil berbentuk meja panjang. Ia menari dengan gerakan kaki dan pinggul ke kanan-kiri, tangan melambai, kadang tegak, kadang membungkuk.
Busananya sederhana, tapi menghadirkan aura yang khas. Kalau kuingat, penari mengenakan sewek (kain) di bagian bawah, kemban di bagian atas, dilengkapi ikat pinggang, sampur, dan kaus kaki putih. Salah satu kakinya dipasangi krincing. Di kepala, ia memakai omprok—hiasan dari daun pisang muda zig-zag, janur, dan bunga segar.
Awalnya, saat baru sampai, aku tak merasakan suasana sakral. Hiruk-piruk penonton membuat suasana hampir lebih mirip festival dibanding ritual. Tapi justru di sanalah hal menarik kutemui: hiburan bisa muncul dari ritual? Menariknya, dalam ritual ini terdapat sesi bernama tundik, yakni saat penari melemparkan sampur ke arah penonton secara acak. Siapa yang terkena, wajib naik panggung dan ikut menari. Jika menolak, konon penari akan marah. Inilah yang menjadi puncak keriuhan! Beberapa penonton terlihat berusaha menghindar, yang lain justru ada yang berharap terkena. Ketika seseorang akhirnya maju ke panggung, sorak-sorai pun membuncah. Teriakan, tawa, sorakan mengisi udara setiap kali sampur dilempar lagi. Sebuah energi kolektif yang tak bisa dibuat-buat.
Wujud Religiusitas Masyarakat
Menjelang petang, suasana berubah. Langit berganti warna, matahari perlahan meluruhkan panasnya. Tak ada lagi lempar sampur, kerumunan mulai menipis. Tapi justru pada saat itulah aku bisa berdiri di barisan paling depan—dan baru mampu merasakan kekhusyukan. Kesakralannya menggema, menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan, hanya mampu dirasakan.
Hal lain yang mencuri perhatianku adalah bentuk panggungnya. Arena Seblang bukanlah panggung megah, melainkan lingkaran di atas tanah lapang. Aku melihatnya sebagai simbol keutuhan dan keterhubungan, karena para penonton mengelilingi sepenuhnya. Meski peminat Seblang Olehsari banyak, bentuk panggung ini tak kehilangan nuansa ritualnya. Di bagian pinggir, panggung dipagari bambu yang mengelilingi arena, sebagai pembatas penonton. Di tengahnya, berdiri sebuah payung besar berwarna putih. Hingga petang, juga tak ada pencahayaan yang berlebihan.
Mulanya saat berada di barisan belakang, tampak anak-anak muda sibuk menjadi panitia. Penjual makanan dan minuman pun ramai berdagang. Namun di barisan depan, yang terlihat justru gotong royong yang menghangat—sebuah semangat menjaga ruang bersama.

Seblang adalah perwujudan kolektif: masyarakat berdoa bersama, ikut mengarak, bahkan ikut menari bila “terpanggil”. Semua menjadi bagian dari ritual. Sebagaimana dalam tulisan Vindriana, Simatupang, dan Richardus (2023:98), penyelenggaraan ritual juga menjadi salah satu wujud religiusitas masyarakat terhadap kekaguman batasan diri terhadap kekuatan-kekuatan di luar dirinya.
Dari Seblang, aku melihat bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Ia bukan semata ritual, melainkan soal kebersamaan, rasa hormat pada asal usul, dan keberanian menjaga yang dipercayai sebagai jalan hidup—meski dunia terus berubah.
Dari siang hingga petang, aku berdiri—mencoba memberi ruang untuk melihat, mendengar, dan memahami sesuatu yang terasa begitu hangat. Upaya manusia untuk hidup bersama, menjaga apa yang mereka anggap penting, dan memberi makna pada waktu yang terus berjalan.
Referensi:
Anoegrajekti, N. (2003). Seblang Using: Studi tentang Ritus dan Identitas Komunitas Using. Jurnal Bahasa dan Seni, Tahun 31, Nomor 2, Agustus 2003, pp. 253-
269.
Scholte, J. 1927. Gandroeng van Banjoewangie. Djawa, VII.
Wolbers, P. A. 1992. Maintaining Using identity through musical performance; Seblang and gandrung of Banyuwangi, East Java (Indonesia). [Ph.D. thesis, University of Illinois, Urbana.].
Wolberes, P. A. 1993. The seblang and its music; Aspects of an East Javanese fertility rite’, in: Bernard Arps (ed.), Performance in Java and Bali, pp. 34-46, London: School of Oriental and African Studies, University of London.
Vindriana, N. D., Simatupang, G. R. L. L., dan Richardus, C. (2023). ‘Festival’ Seblang Olehsari Banyuwangi 2018-2022. Jurnal Kajian Seni, Volume 10, Nomo 01, November 2023, pp. 94-115. DOI: https://doi.org/10.22146/jksks.80959.
Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.